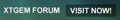


Kiyai, penyair, novelis,
pelukis, budayawan dan
cendekiawan muslim, ini telah
memberi warna baru pada
peta perjalanan kehidupan
sosial dan politik para ulama.
Ia kiyai yang bersahaja, bukan
kiyai yang ambisius. Ia kiyai
pembelajar bagi para ulama
dan umat. Pengasuh Pondok
Pesantren Roudlatut Thalibin,
Rembang, Jawa Tengah, ini
enggan (menolak) dicalonkan
menjadi Ketua Umum PB
Nahdlatul Ulama dalam
Muktamar NU ke-31
28/11-2/12-2004 di Boyolali,
Jawa Tengah.
KH Achmad Mustofa Bisri,
akrab dipanggil Gus Mus, ini
mempunyai prinsip harus bisa
mengukur diri. Setiap hendak
memasuki lembaga apapun, ia
selalu terlebih dahulu
mengukur diri. Itulah yang
dilakoninya ketika Gus Dur
mencalonkannya dalam
pemilihan Ketua Umum PB
Nahdlatul Ulama pada
Muktamar NU ke-31 itu.
“Saya harus bisa mengukur
diri sendiri. Mungkin lebih baik
saya tetap berada di luar,
memberikan masukan dan
kritikan dengan cara saya,”
jelas alumnus Al Azhar
University, Kairo (Mesir), ini,
yang ketika kuliah mempunyai
hobi main sepakbola dan
bulutangkis. Setelah tak lagi
punya waktu meneruskan hobi
lamanya, ulama ini lalu
menekuni hobi membaca buku
sastra dan budaya, menulis
dan memasak, termasuk
masak makanan Arab dengan
bumbu tambahan.
Lahir di Rembang, Jawa
Tengah, 10 Agustus 1944, dari
keluarga santri. Kakeknya,
Kyai Mustofa Bisri adalah
seorang ulama. Demikian pula
ayahnya, KH Bisri Mustofa,
yang tahun 1941 mendirikan
Pondok Pesantren Roudlatut
Thalibin, adalah seorang
ulama karismatik termasyur.
Ia dididik orangtuanya dengan
keras apalagi jika menyangkut
prinsip-prinsip agama. Namun,
pendidikan dasar dan
menengahnya terbilang
kacau. Setamat sekolah dasar
tahun 1956, ia melanjut ke
sekolah tsanawiyah. Baru
setahun di tsanawiyah, ia
keluar, lalu masuk Pesantren
Lirboyo, Kediri selama dua
tahun. Kemudian pindah lagi
ke Pesantren Krapyak,
Yogyakarta. Di Yogyakarta, ia
diasuh oleh KH Ali Maksum
selama hampur tiga tahun. Ia
lalu kembali ke Rembang
untuk mengaji langsung diasuh
ayahnya.
KH Ali Maksum dan ayahnya
KH Bisri Mustofa adalah guru
yang paling banyak
mempengaruhi perjalanan
hidupnya. Kedua kiyai itu
memberikan kebebasan
kepada para santri untuk
mengembangkan bakat seni.
Kemudian tahun 1964, dia
dikirim ke Kairo, Mesir,
belajar di Universitas Al-
Azhar, mengambil jurusan
studi keislaman dan bahasa
Arab, hingga tamat tahun
1970. Ia satu angkatan dengan
KH Abdurrahman Wahid (Gus
Dur).
Menikah dengan Siti Fatimah,
ia dikaruniai tujuh orang anak,
enam di antaranya
perempuan. Anak lelaki satu-
satunya adalah si bungsu
Mochamad Bisri Mustofa, yang
lebih memilih tinggal di
Madura dan menjadi santri di
sana. Kakek dari empat cucu
ini sehari-hari tinggal di
lingkungan pondok hanya
bersama istri dan anak
keenamnya Almas.
Setelah abangnya KH Cholil
Bisri meninggal dunia, ia
sendiri memimpin dan
mengasuh Pondok Pesantren
Roudlatut Thalibin, didampingi
putra Cholil Bisri. Pondok yang
terletak di Desa Leteh,
Kecamatan Rembang Kota,
Kabupaten Rembang, Jawa
Tengah, 115 kilometer arah
timur Kota Semarang, itu
sudah berdiri sejak tahun
1941.
Keluarga Mustofa Bisri
menempati sebuah rumah
kuno wakaf yang tampak
sederhana tapi asri, terletak
di kawasan pondok. Ia biasa
menerima tamu di ruang
seluas 5 x 12 meter berkarpet
hijau dan berisi satu set kursi
tamu rotan yang usang dan
sofa cokelat. Ruangan tamu
ini sering pula menjadi tempat
mengajar santrinya.
Pintu ruang depan rumah
terbuka selama 24 jam bagi
siapa saja. Para tamu yang
datang ke rumah lewat
tengah malam bisa langsung
tidur-tiduran di karpet, tanpa
harus membangunkan
penghuninya. Dan bila subuh
tiba, keluarga Gus Mus akan
menyapa mereka dengan
ramah. Sebagai rumah wakaf,
Gus Mus yang rambutnya
sudah memutih berprinsip,
siapapun boleh tinggal di situ.
Di luar kegiatan rutin sebagai
ulama, dia juga seorang
budayawan, pelukis dan
penulis. Dia telah menulis
belasan buku fiksi dan
nonfiksi. Justru melalui karya
budayanyalah, Gus Mus sering
kali menunjukkan sikap
kritisnya terhadap “budaya”
yang berkembang dalam
masyarakat. Tahun 2003,
misalnya, ketika goyang
ngebor pedangdut Inul
Daratista menimbulkan pro
dan kontra dalam
masyarakat, Gus Mus justru
memamerkan lukisannya yang
berjudul “Berdzikir Bersama
Inul”. Begitulah cara Gus Mus
mendorong “perbaikan”
budaya yang berkembang saat
itu.
Bakat lukis Gus Mus terasah
sejak masa remaja, saat
mondok di Pesantren Krapyak,
Yogyakarta. Ia sering
keluyuran ke rumah-rumah
pelukis. Salah satunya
bertandang ke rumah sang
maestro seni lukis Indonesia,
Affandi. Ia seringkali
menyaksikan langsung
bagaimana Affandi melukis.
Sehingga setiap kali ada
waktu luang, dalam bantinnya
sering muncul dorongan
menggambar. “Saya ambil
spidol, pena, atau cat air
untuk corat-coret. Tapi kumat-
kumatan, kadang-kadang, dan
tidak pernah serius,” kata Gus
Mus, perokok berat yang
sehari-hari menghabiskan dua
setengah bungkus rokok.
Gus Mus, pada akhir tahun
1998, pernah memamerkan
sebanyak 99 lukisan amplop,
ditambah 10 lukisan bebas dan
15 kaligrafi, digelar di Gedung
Pameran Seni Rupa,
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Jakarta. Kurator
seni rupa, Jim Supangkat,
menyebutkan, kekuatan
ekspresi Mustofa Bisri
terdapat pada garis grafis.
Kesannya ritmik menuju zikir
membuat lukisannya beda
dengan kaligrafi. “Sebagian
besar kaligrafi yang ada
terkesan tulisan yang diindah-
indahkan,” kata Jim
Supangkat, memberi apresiasi
kepada Gus Mus yang pernah
beberapa kali melakukan
pameran lukisan.
Sedangkan dengan puisi, Gus
Mus mulai mengakrabinya
saat belajar di Kairo, Mesir.
Ketika itu Perhimpunan
Pelajar Indonesia di Mesir
membikin majalah. Salah satu
pengasuh majalah adalah Gus
Dur. Setiap kali ada halaman
kosong, Mustofa Bisri diminta
mengisi dengan puisi-puisi
karyanya. Karena Gus Dur
juga tahu Mustofa bisa
melukis, maka, ia diminta
bikin lukisan juga sehingga
jadilah coret-coretan, atau
kartun, atau apa saja, yang
penting ada gambar pengisi
halaman kosong. Sejak itu,
Mustofa hanya menyimpan
puisi karyanya di rak buku.
Namun adalah Gus Dur pula
yang ‘mengembalikan’ Gus
Mus ke habitat perpuisian.
Pada tahun 1987, ketika
menjadi Ketua Dewan
Kesenian Jakarta, Gus Dur
membuat acara “Malam
Palestina”. Salah satu mata
acara adalah pembacaan puisi
karya para penyair Timur
Tengah. Selain pembacaan
puisi terjemahan, juga
dilakukan pembacaan puisi
aslinya. Mustofa, yang fasih
berbahasa Arab dan Inggris,
mendapat tugas membaca
karya penyair Timur Tengah
dalam bahasa aslinya. Sejak
itulah Gus Mus mulai bergaul
dengan para penyair.
Sejak Gus Mus tampil di
Taman Ismail Marzuki, itu
kepenyairannya mulai
diperhitungkan di kancah
perpuisian nasional. Undangan
membaca puisi mengalir dari
berbagai kota. Bahkan ia juga
diundang ke Malaysia, Irak,
Mesir, dan beberapa negara
Arab lainnya untuk berdiskusi
masalah kesenian dan
membaca puisi. Berbagai
negeri telah didatangi kyai
yang ketika muda pernah
punya keinginan aneh, yakni
salaman dengan Menteri
Agama dan menyampaikan
salam dari orang-orang di
kampungnya. Untuk maksud
tersebut ia berkali-kali datang
ke kantor sang menteri.
Datang pertama kali, ditolak,
kedua kali juga ditolak.
Setelah satu bulan, ia
diizinkan ketemu menteri
walau hanya tiga menit.
Kyai bertubuh kurus
berkacamata minus ini telah
melahirkan ratusan sajak yang
dihimpun dalam lima buku
kumpulan puisi: Ohoi,
Kumpulan Puisi Balsem (1988),
Tadarus Antologi Puisi (1990),
Pahlawan dan Tikus (1993),
Rubaiyat Angin dan Rumput
(1994), dan Wekwekwek
(1995). Selain itu ia juga
menulis prosa yang dihimpun
dalam buku Nyamuk Yang
Perkasa dan Awas Manusia
(1990).
Tentang kepenyairan Gus Mus,
‘Presiden Penyair Indonesia’
Sutardji Calzoum Bachri
menilai, gaya pengucapan
puisi Mustofa tidak berbunga-
bunga, sajak-sajaknya tidak
berupaya bercantik-cantik
dalam gaya pengucapan. Tapi
lewat kewajaran dan
kesederhanaan berucap atau
berbahasa, yang tumbuh dari
ketidakinginan untuk
mengada-ada. Bahasanya
langsung, gamblang, tapi
tidak menjadikan puisinya
tawar atau klise. “Sebagai
penyair, ia bukan penjaga
taman kata-kata. Ia penjaga
dan pendamba kearifan,” kata
Sutardji.
Kerap memberi ceramah dan
tampil di mimbar seminar
adalah lumrah bagi Gus Mus.
Yang menarik, pernah dalam
sebuah ceramah, hadirin
meminta sang kiai
membacakan puisi. Suasana
hening. Gus Mus lalu beraksi:
“Tuhan, kami sangat sibuk.
Sudah.”
Sebagai cendekiawan muslim,
Gus Mus mengamalkan ilmu
yang didapat dengan cara
menulis beberapa buku
keagamaan. Ia termasuk
produktif menulis buku yang
berbeda dengan buku para
kyai di pesantren. Tahun 1979,
ia bersama KH M. Sahal
Mahfudz menerjemahkan
buku ensiklopedia ijmak. Ia
juga menyusun buku tasawuf
berjudul Proses Kebahagiaan
(1981). Selain itu, ia menyusun
tiga buku tentang fikih yakni
Pokok-Pokok Agama (1985),
Saleh Ritual, Saleh Sosial
(1990), dan Pesan Islam
Sehari-hari (1992).
Ia lalu menerbitkan buku
tentang humor dan esai,
“Doaku untuk Indonesia” dan
“Ha Ha Hi Hi Anak Indonesia”.
Buku yang berisi kumpulan
humor sejak zaman Rasullah
dan cerita-cerita lucu
Indonesia. Menulis kolom di
media massa sudah
dimulainya sejak muda.
Awalnya, hatinya “panas” jika
tulisan kakaknya, Cholil Bisri,
dimuat media koran lokal dan
guntingan korannya ditempel
di tembok. Ia pun tergerak
untuk menulis. Jika dimuat,
guntingan korannya ditempel
menutupi guntingan tulisan
sang kakak. Gus Mus juga
rajin membuat catatan harian.
Seperti kebanyakan kyai
lainnya, Mustofa banyak
menghabiskan waktu untuk
aktif berorganisasi, seperti di
NU. Tahun 1970, sepulang
belajar dari Mesir, ia menjadi
salah satu pengurus NU
Cabang Kabupaten Rembang.
Kemudian, tahun 1977, ia
menduduki jabatan Mustasyar,
semacam Dewan Penasihat
NU Wilayah Jawa Tengah.
Pada Muktamar NU di
Cipasung, Jawa Barat, tahun
1994, ia dipercaya menjadi
Rais Syuriah PB NU.
Enggan Ketua PB NU
Kesederhanaannya telah
memberi warna baru pada
peta perjalanan kehidupan
sosial dan politik para ulama.
Ia didorong-dorong oleh Gus
Dur dan kawan-kawan dari
kelompok NU kultural, untuk
mau mencalonkan diri sebagai
calon ketua umum PB NU
pada Muktamar NU ke-31
tahun 2004, di Boyolali, Jawa
Tengah. Tujuannya, untuk
menandingi dan menghentikan
langkah maju KH Hasyim
Muzadi dari kelompok NU
struktural. Kawan karib Gus
Dur selama belajar di Kairo,
Mesir, ini dianggap salah satu
ulama yang berpotensi
menghentikan laju ketua
umum lama. Namun Gus Mus
justru bersikukuh menolak.
Alhasil, Hasyim Muzadi
mantan calon wakil presiden
berpasangan dengan calon
presiden Megawati
Soekarnoputri dari PDI
Perjuangan, pada Pemilu
Preisden 2004, itu terpilih
kembali sebagai Ketua Dewan
Tanfidziah ‘berpasangan’
dengan KH Achmad Sahal
Makhfud sebagai Rois Aam
Dewan Syuriah PB NU.
Muktamar berhasil
meninggalkan catatan
tersendiri bagi KH Achmad
Mustofa Bisri, yakni ia berhasil
menolak keinginan kuat Gus
Dur, ulama ‘kontroversial’.
Ternyata langkah seperti itu
bukan kali pertama
dilakukannya. Jika tidak
merasa cocok berada di suatu
lembaga, dia dengan elegan
menarik diri. Sebagai misal,
kendati pernah tercatat
sebagai anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Jawa Tengah tahun
1987-1992, mewakili PPP,
demikian pula pernah sebagai
anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat
(MPR), mantan Rois Syuriah
PB NU periode 1994-1999 dan
1999-2004 ini tidak pernah mau
dicalonkan untuk menjabat
kembali di kedua lembaga
tersebut. Lalu, ketika NU
ramai-ramai mendirikan partai
PKB, ia tetap tak mau turun
gelanggang politik apalagi
terlibat aktif di dalamnya.
Demikian pula dalam Pemilu
Legislatif 2004, meski
namanya sudah ditetapkan
sebagai calon anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) dari
Jawa Tengah, ia lalu memilih
mengundurkan diri sebelum
pemilihan itu sendiri digelar.
Ia merasa dirinya bukan orang
yang tepat untuk memasuki
bidang pemerintahan. Ia
merasa, dengan menjadi wakil
rakyat, ternyata apa yang
diberikannya tidak sebanding
dengan yang diberikan oleh
rakyat. “Selama saya menjadi
anggota DPRD, sering terjadi
pertikaian di dalam batin
saya, karena sebagai wakil
rakyat, yang menerima lebih
banyak dibandingkan dengan
apa yang bisa saya berikan
kepada rakyat Jawa Tengah,”
kata Mustofa mengenang
pengalaman dan pertentangan
batin yang dia alami selama
menjadi politisi.
Dicalonkan menjadi ketua
umum PB NU sudah seringkali
dialami Gus Mus. Dalam
beberapa kali mukhtamar,
namanya selalu saja dicuatkan
ke permukaan. Ia adalah
langganan “calon ketua
umum” dan bersamaan itu ia
selalu pula menolak. Di
Boyolali 2004 namanya
digandang-gandang sebagai
calon ketua umum. Bahkan
dikabarkan para kyai sepuh
telah meminta kesediaannya.
Sampai-sampai utusan kyai
sepuh menemui ibunya,
Ma’rafah Cholil, agar
mengizinkan anaknya
dicalonkan. Sang ibu malah
hanya menjawab lugas khas
warga ulama NU, ”Mustofa itu
tak jadi Ketua Umum PB NU
saja sudah tak pernah di
rumah, apalagi kalau menjadi
ketua umum. Nanti saya tak
pernah ketemu.”
Gus Mus sendiri yang tampak
enggan dicalonkan, dengan
tangkas menyebutkan, “Saya
mempunyai hak prerogatif
untuk menolak,” ucap pria
bertutur kata lembut yang
sesungguhnya berkawan karib
dengan Gus Dur selama
belajar di Kairo, Mesir. Saking
karibnya, Gus Mus pernah
meminta makan kepada Gus
Dur selama berbulan-bulan
sebab beasiswanya belum
turun-turun. Persahabatan
terus berlanjut sampai
sekarang. Kalau Gus Dur
melawat ke Jawa Timur dan
singgah di Rembang, biasanya
mampir ke rumah Gus Mus.
Sebaliknya, bila dia
berkunjung ke Jakarta, sebisa-
bisanya bertandang ke rumah
Gus Dur. Selain saling
kunjung, mereka tak jarang
pula berkomunikasi melalui
telepon.
HOME